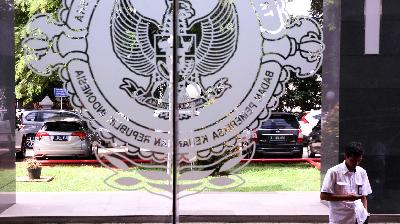Kembalikan Politik kepada Publik
Mahkamah Konstitusi mengembalikan politik kepada publik. Tapi pemilih kembali menjadi penonton sirkus politik yang banal.
arsip tempo : 172641420749.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan kepala daerah mengembalikan rasionalitas politik yang sebelumnya dibajak partai. Demokrasi yang redup kini sedikit menyala lagi. Publik yang tersingkir dari ingar-bingar pemilihan kepala daerah melihat cahaya di ujung lorong—kesempatan terlibat dalam proses demokrasi tersebut.
Dengan persyaratan yang berat, minimal 20 persen kursi di dewan perwakilan rakyat daerah atau 25 persen suara sah, partai atau gabungan partai politik sulit menyorongkan calon sendiri. Apalagi jika ada yang membentuk koalisi besar dengan memborong hampir semua partai seperti yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju plus, gabungan partai pendukung Prabowo Subianto garis miring Joko Widodo. Ini menyebabkan partai yang ingin mengusung calon sendiri terkucil karena tak memiliki cukup kursi atau suara.
Akibatnya, pemilih tak punya banyak alternatif. Sebelum putusan MK terbit, potensi kotak kosong sebagai lawan calon kepala daerah diperkirakan ada di 150 dari 545 daerah pemilihan. Calon kepala daerah pun diusung koalisi tak lagi berdasarkan aspirasi pemilih, melainkan kemauan para juragan partai. Elektabilitas tak lagi penting karena kandidat dengan tingkat keterpilihan tinggi tak bisa maju lantaran tak punya perahu.
Putusan MK membuyarkan skenario KIM plus menguasai daerah dan melanggengkan dinasti politik. Rencana koalisi ini merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan mengabaikan putusan MK disiapkan agar skenario awal tetap berjalan. Partai politik mempertontonkan diri sebagai begal konstitusi sekaligus begal kehendak publik.
Pada akhirnya, setelah khalayak turun ke jalan dan mengepung gedung DPR, pemerintah dan semua partai mengikuti putusan MK. Dengan ambang batas yang lebih ringan, kesempatan partai mengusung calon sendiri menjadi terbuka.
Dalam putusannya, MK sebenarnya mengembalikan politik kepada publik—dengan menyandarkan persentase ambang batas pada jumlah pemilih di suatu daerah, bukan kursi di DPRD. Namun, sesungguhnya, penerima manfaat terbesar putusan ini adalah elite partai. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk memenuhi kepentingan, termasuk berkompromi dengan rival. Publik lagi-lagi hanya menjadi penonton pertunjukan politik yang banal.
Semua ini tak akan terjadi jika dari awal syarat mengusung calon kepala daerah tak memakai ambang batas sama sekali. Selain akan meminimalkan transaksi politik di antara partai, hal itu akan memberikan banyak pilihan calon pemimpin daerah bagi pemilih. Dengan alternatif yang lebih terbuka, penguasa atau siapa pun tak gampang memborong partai untuk menjegal calon tertentu.
Orang yang tak setuju atas usul ini akan berargumen bahwa ketiadaan ambang batas akan menyebabkan peserta pemilihan kepala daerah membeludak: pemilu jadi proses yang merepotkan dan mahal. Kandidat perlu mengeluarkan uang lebih karena tidak sedang bersaing dengan satu-dua kompetitor. Politik uang merajalela karena tiap calon berlomba merayu pemilih dengan fulus dan iming-iming.
Alasan ini mungkin ada benarnya. Tapi politik uang, betapapun nistanya, sulit efektif jika dilakukan pada obyek yang tersebar. Makin banyak kandidat, makin repot kartel politik mengendalikan kandidat.
Dengan banyak calon kepala daerah, persaingan akan lebih fair dan terbuka. Calon kepala daerah harus membangun rekam jejak agar dikenal masyarakat. Jalan pintas meroketkan elektabilitas dengan bagi-bagi bahan kebutuhan pokok, misalnya, sulit efektif karena boleh jadi ada kandidat lain yang mendapatkan simpati karena rekam jejak yang baik. Soal biaya kampanye yang tinggi bisa diatasi dengan pembatasan medium kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka yang nakal karena menerima sumbangan di atas batas maksimal dapat dikenai pasal pidana.
Bola untuk mengubah ambang batas telah disepak MK. Keputusan menihilkan ambang batas kini ada di tangan elite politik dan DPR. Jika berkomitmen pada demokrasi dan mengutamakan publik dalam proses politik, partai semestinya tak keberatan atas gagasan ini. Ambang batas dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, ataupun pemilihan presiden—juga syarat pendirian partai politik—telah menyebabkan ruang elektoral menyempit yang menuntun pada kemunduran demokrasi.