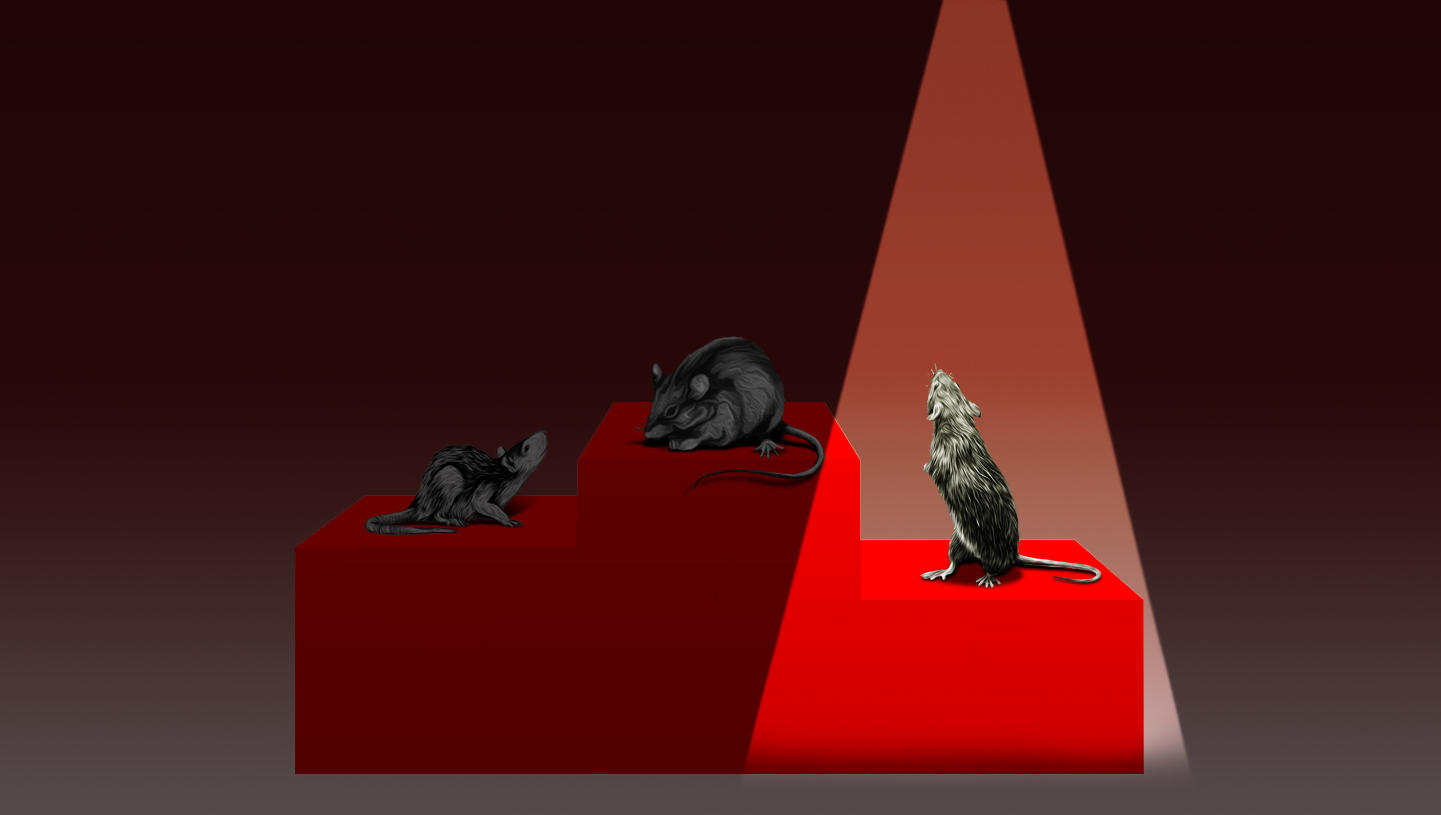Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lahir: 1927, meninggal pekan lalu.
Gunter Grass membaca sajak. Saya mendengarkannya di pertemuan puisi di Rotterdam, Juni 1973. Pelan, seolah-olah tiap kalimat membebani rahangnya dan membuat wajahnya yang masam bertambah masam.
Nun zogen sie durch die Strassen, 3800 Propheten...
(Kini bergeraklah mereka di jalan-jalan, 3800 Nabi...)
Tak ada melodi. Tapi imaji yang bermunculan dari sajak itu tak mudah saya lupakan (saya masih simpan teks Prophetenkost): belalang yang menyerbu kota, rumah yang kehabisan air susu, rasul-rasul yang dilepas dari kurungan, 3800 nabi yang menghambur ke jalan, warna abu-abu yang menutupi permukaan dan "bernama sampar".
Sebuah sajak pendek, sebuah gambaran tentang adegan yang menakutkan -- mungkin tulah Tuhan dari langit -- yang seakan-akan diambil dari lukisan religius Hieronymus Bosch di abad ke-15. Kesan utamanya visual, ciri puisi Grass sejak ia belajar di Akademi Senirupa di Dusseldorf. Warna surrealismenya kuat, seperti dalam buku pertamanya, Die Vorzuge der Windhuhner,(1956): interaksi kata dan gambar yang mencoba merekam mimpi yang aneh. Gambar-gambar Grass adalah goresan fantasi tentang burung dan hewan buas, sajak-sajaknya menghidupkan benda-benda yang dijumpai secara acak, saat yang tak disengaja.
Di Rotterdam malam itu Grass membaca beberapa sajak lagi. Tetap membosankan. Tapi ia tetap mampu menghadirkan apa yang ganjil, gelap, kadang-kadang kalut, ironis, kocak, atau mengusik. Ia seorang Kafka dalam puisi. Ia membebaskan bahasa dari arah yang harus lurus, dari makna yang didikte tujuan, pesan, dan slogan, dari susunan kalimat yang lelah seperti serdadu yang capek karena menghentakkan sepatu terus-menerus.
Dalam sajak Grass, seperti dalam novelnya yang menakjubkan itu, Die Blechtrommel, (versi bahasa Inggrisnya: The Tin Drum), hidup dibuat terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa -- yang sering disangka sebagai dusta. Dalam campuran karya realis dan magis ini, kita menerima Oskar Matzerath, anak yang menolak tumbuh dewasa, dengan suara teriak yang bisa meretakkan cermin, yang selalu siap dengan genderang mainan tapi dengan nafsu syahwat orang dewasa.
"Ketika saya anak-anak, saya pendusta besar", kata Grass dalam sebuah wawancara. Tapi ia memilih "dusta yang tak melukai orang lain"-- dusta yang kita perlukan untuk mendampingi kebenaran. Sebab, kata Grass, "kebenaran sering membosankan."
Tapi sesekali penyair perlu juga membosankan.
Di tahun 2012 Grass menulis Was gesagt werden muss (Apa yang musti dikatakan) dalam koran Suddeutsche Zeitung. Sajak itu membuat heboh karena benar, dan karena buruk.
Ia ingin tak berbohong:
Kenapa aku baru sekarang bicara,
di umur tua, dengan tetes tinta terakhir:
bahwa kekuatan nuklir Israel
adalah ancaman perdamaian dunia?
Dengan segera, pemerintah Israel marah. Grass jadi persona-non-grata. Masa lalunya digugat: ia pernah ikut bergabung dengan pasukan Waffen-SS di masa Nazi. Tentu saja ia dituduh "anti-Semit". Banyak orang yang semula mengagumi pemenang Hadiah Nobel 1999 itu menyalahkannya.
Tapi adakah yang mesti disalahkan? Sajak itu benar. Sudah sepatutnya seseorang mengecam hipokrisi Amerika dan Eropa yang membiarkan Israel menyembunyikan senjata nuklirnya tapi melarang Iran mendapatkannya.
Meskipun demikian, benar saja tak cukup. "Was gesagt werden muss" diangkat dengan bentuk yang salah. Grass seharusnya menulis petisi, dan bukan sebuah sajak yang buruk, bila ia ingin mengerahkan kata-kata untuk menyatakan sebuah kebenaran dan menyelamatkan kehidupan.
Tapi tampaknya ia ingin menunjukkan ia bisa bikin puisi yang sanggup menggugah dunia, puisi yang juga laku politik. Barangkali ia kadang-kadang lupa: politik yang terbaik ialah politik yang tak dibikin sentimental karena puisi, dan puisi terbaik adalah yang tak direcoki keinginan melayani program politik.
Grass sebenarnya sudah membuktikan itu dengan dirinya. Sajak yang dibacanya di malam itu kuat, justru ketika ia aktif dalam politik mendukung Partai Sosialis Demokrat di bawah Willy Brandt.
Bagaimana ia menjaga demarkasi itu pasti soal yang menarik.
Tapi saya tak menanyakannya ketika kami duduk, minum-minum, di antara para penyair lain yang datang untuk pertemuan internasional baca puisi itu. Bahasa Jerman saya, yang sangat terbatas, hanya dia pahami 10 %, dan bahasa Jermannya saya pahami 20%. Waktu itu dia lebih mencoba sopan dengan menanyakan sedikit banyak soal Indonesia yang berada di bawah kediktaturan militer, tapi saya tahu ia lebih tertarik kepada India.
Beberapa tahun kemudian, pada usia 85, bisa dimengerti bila ia sesekali terpeleset ke dalam ilusi. Di masa lalunya ilusi itu belum ada, ketika ia mengagumi Gottfried Benn, penyair ekspresionis yang hidup mengalami dua perang besar, seorang pendukung Hitler yang kecewa. Bagi Benn, karya seni punya arti justru karena ia "secara historis tak efektif", puisi bernilai justru karena tak punya akibat praktis.
Tapi Grass tak hanya melihat ke arah Benn. Ia juga melihat ke arah Bertold Brecht, dramawan Marxis yang yakin bahwa karya teaternya bisa "mengubah kenyataan". Ada yang mengatakan Grass ingin jadi persilangan antara kedua pandangan itu. Tapi agaknya bukan sang sastrawan yang menentukan ke sebelah mana novel dan puisinya condong.
Dalam Mein Jahrhundret, Grass menggambarkan pertemuan imajiner antara Benn dan Brecht. Seorang mahasiswa menguping percakapan mereka. Yang ia dapatkan sebuah ironi: kedua sastrawan tenar itu tahu bahwa pembaca, bukan mereka, yang membentuk arah mereka. Selalu ada jarak, selalu ada selisih, dan mereka tak akan dapat mengendalikannya. "Siapa yang akan melindungi kita dari para epigon kita?". Selalu sang sastrawan tak bisa apa-apa lagi. Mungkin karena di jalan ada suara 38000 nabi.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo